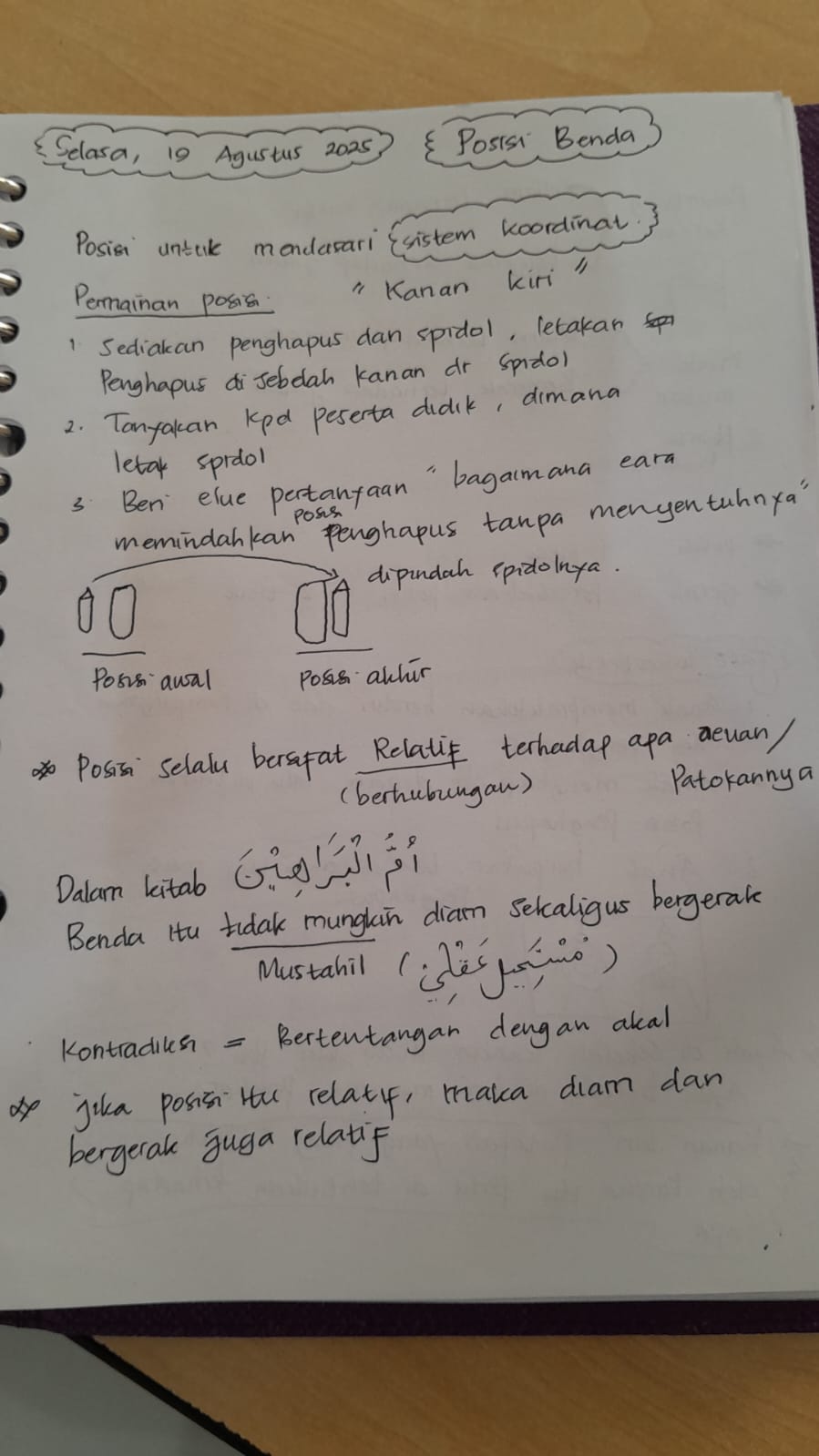
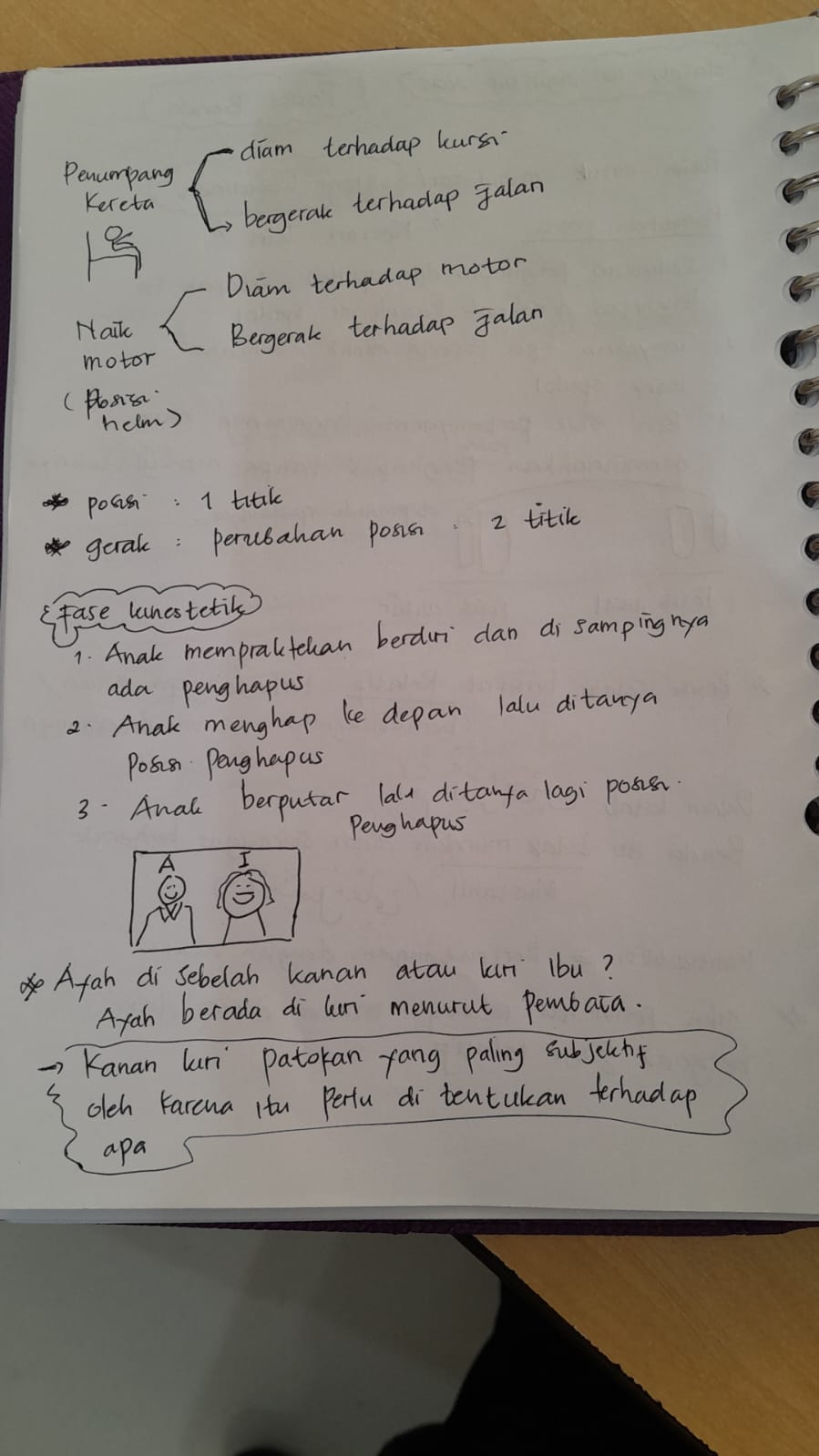
Apa yang teman-teman ikuti: kitab aqidah Ummul Barāhin, ataukah fisika yang merupakan pemimpin sains?
Hari itu, tim Matematika Titik Sekolah Al Biruni sedang mendiskusikan tentang posisi, yaitu bagian dari materi matematika kelas 2 SD. Meski tampak sederhana, posisi adalah tema terpenting dalam fisika, karena darinya lahir pemahaman tentang diam dan gerak. Dan ketika bahasan ini muncul di ruang kelas, ia tidak hanya menjadi soal pedagogi, tapi juga medan pertempuran epistemik—karena harus berhadapan langsung dengan penyebaran kesesatan oleh para agamawan yang mengklaim aqidah sebagai fondasi nalar, padahal justru merusaknya.
Fisika adalah sains yang paling kokoh dalam sejarah peradaban manusia. Ia tidak dibangun di atas keyakinan dogmatis, melainkan di atas observasi yang cermat, eksperimen yang terukur, dan pemikiran yang jernih. Namun justru karena kokohnya, fisika bukan ilmu yang mudah. Kesulitan utama fisika terletak pada tuntutannya terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi—kritis, logis, sistematis, dan kreatif—yang harus dikombinasikan dengan keterampilan proses ilmiah seperti observasi, pengukuran, dan eksperimen yang presisi. Fisika tidak hanya menuntut pemahaman konsep, tetapi juga kemampuan untuk memodelkan fenomena alam yang kompleks secara matematis dan mengujinya secara empiris. Inilah yang membuat fisika menjadi medan intelektual yang paling menantang sekaligus paling mendidik.
Salah satu fondasi fisika adalah kinematika—ilmu tentang posisi, gerak, dan diam. Tiga konsep ini tampak sederhana, tapi sesungguhnya adalah pintu masuk menuju seluruh bangunan fisika klasik dan modern. Dan di sinilah masalah besar muncul ketika teks aqidah klasik seperti Ummul Barāhin menyatakan:
واعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي الثلاثة، فالواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم، والمستحيل نفيهما معا عن الجرم، والجائز ثبوت أحدهما بالخصوص للجرم.
“Ketahuilah bahwa gerak dan diam suatu benda dapat digunakan sebagai representasi bagi tiga kategori hukum akal:
- Wajib menurut akal adalah menetapkan salah satunya (gerak atau diam) tanpa menentukan secara spesifik bagi benda.
- Mustahil menurut akal adalah meniadakan keduanya sekaligus dari benda.
- Jaiz menurut akal adalah menetapkan salah satunya secara khusus bagi benda.”
Pernyataan ini tampak logis secara tekstual, namun cacat secara operasional. Ia mengasumsikan bahwa gerak dan diam adalah keadaan mutlak yang bisa dilekatkan pada benda secara independen. Padahal, dalam fisika—bahkan sejak Galileo dan Newton—gerak dan diam selalu bersifat relatif terhadap kerangka acuan. Ketika aqidah memutlakkan apa yang dalam fisika justru bersifat relasional, maka ia bukan sedang membimbing nalar, melainkan sedang merusaknya.
Bayangkan seorang penumpang duduk tenang di dalam KA Kaligung yang melaju dari Tegal ke Semarang. Bagi penumpang lain di dalam KA, ia tampak diam. Bagi pengamat di luar KA, ia bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kereta. Bagi pengamat di pesawat yang terbang di atas rel, posisi dan kecepatannya akan berbeda lagi. Maka, gerak dan diam bukanlah sifat mutlak benda, melainkan relasi antara benda dan pengamat. Tidak mungkin menetapkan gerak atau diam secara absolut, dan tidak mungkin meniadakan keduanya sekaligus, karena setiap benda pasti memiliki posisi relatif terhadap sesuatu.
Bahasan tentang posisi, diam, dan gerak bukan sekadar bagian dari fisika modern, melainkan fondasi seluruh fisika. Dalam buku Fisika Dasar 1, dijelaskan bahwa gerak benda selalu dianalisis terhadap sistem koordinat atau kerangka acuan tertentu. Dalam Seri Sains: Gaya dan Gerak, gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi terhadap titik acuan. Dalam Relativitas Khusus, gerak dan diam menjadi sepenuhnya relatif: tidak ada kerangka acuan absolut. Dalam Relativitas Umum, bahkan ruang-waktu itu sendiri melengkung, dan gerak benda bergantung pada geometri serta distribusi massa-energi.
Menariknya, prinsip relativitas ini bukan hanya milik fisika modern. Ia telah tersirat dalam wahyu. Dalam QS. As-Sajdah:5, Allah berfirman:
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”
Dan dalam QS. Al-Ma’arij:4 ditegaskan:
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
“Para malaikat dan Ruh naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.”
Dua ayat ini menunjukkan bahwa waktu tidak bersifat mutlak. Satu hari dalam sistem langit bisa setara dengan seribu atau lima puluh ribu tahun dalam sistem bumi. Ini bukan sekadar metafora, melainkan pengakuan eksplisit bahwa waktu dan gerak bersifat relatif terhadap sistem dan pengamatnya. Maka, ketika fisika menyatakan bahwa gerak dan waktu adalah fungsi dari kerangka acuan, bagi seorang muslim, hal itu merupakan detail-operasional wahyu guna membangun peradaban.
Filsafat sains modern menegaskan bahwa tidak ada “pengamatan murni” tanpa kerangka. Semua observasi bersifat teoritis—terikat pada sistem, alat ukur, dan posisi pengamat. Maka, menyatakan bahwa suatu benda “harus” diam atau bergerak secara mutlak adalah bentuk penyimpangan epistemik. Ketika pendidikan aqidah tidak tunduk pada prinsip kerja logika dan sains, maka ia bukan lagi cahaya bagi akal, melainkan kabut yang menutupi jalan berpikir.
Jika aqidah hendak menjadi fondasi nalar, maka ia harus tunduk pada prinsip-prinsip epistemik yang sahih dan operasional. Menyatakan bahwa gerak atau diam adalah “wajib” bagi benda tanpa menyebut kerangka acuan bukanlah bentuk ketegasan ilmiah, melainkan bentuk penyimpangan logika yang berbahaya. Ia mengajarkan umat untuk berpikir tanpa observasi, tanpa verifikasi, dan tanpa kesadaran akan relativitas posisi.
Dan kini, kita dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa dihindari. Apakah kita akan membiarkan kesesatan epistemik dalam kitab Ummul Barāhin terus didakwahkan sebagai fondasi aqidah selama lebih dari 500 tahun, tanpa koreksi, tanpa klarifikasi, bahkan tanpa keberanian untuk menguji ulang klaimnya? Ataukah kita akan membuka jalan bagi pendidikan aqidah yang baru—yang tidak hanya menjaga integritas iman, tetapi juga mampu menjadi fondasi bagi logika, matematika, dan sains; aqidah yang tidak memutlakkan apa yang relatif, tidak meniadakan apa yang teramati, dan tidak membungkam nalar atas nama sanad dan warisan (turats)?
Karena jika aqidah adalah cahaya, maka ia harus mampu menerangi jalan berpikir. Dan jika ia adalah fondasi, maka ia harus kokoh menopang bangunan ilmu, bukan meretakkannya dari dalam. Pilihan ada di tangan kita: melanjutkan warisan tanpa verifikasi, atau membangun ulang fondasi dengan kejernihan dan keberanian epistemik.